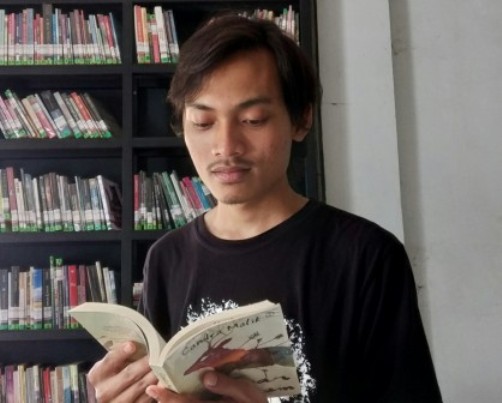Seseorang yang Memesan Sepi
Hendy Pratama, Senang menulis. Beberapa catatannya masih banyak terdokumentasi sebagai catatan pribadi. Kini masih tercatat sebagai mahasiswa hukum IAIN Ponorogo, Jawa Timur.
AKU tak tahu harus bercerita dari mana. Sebab, aku juga tak tahu harus bercerita dengan siapa. Semua menjadi padu; satu kesatuan yang utuh antara cerita dengan seseorang. Aku harus bangun. Tak mungkin aku masih tetap tidur di sini. Tak mungkin aku akan menjadi seorang pemuda yang rela menghabiskan waktunya hanya untuk tidur. Namun, aku masih bingung. Aku ingin bercerita kepada seseorang. Tetapi tak tahu kepada siapa. Oleh sebab itulah, aku bermaksud untuk memesan sepi.
***
AKU adalah seorang pendiam, selayaknya batang yang tak pernah berucap tatkala daun jatuh dari rantingnya. Begitulah kiranya diriku. Di usiaku yang sudah berkepala tiga ini, aku masih bujang. Tak ada sosok perempuan yang singgah di relung hatiku. Atau perempuan yang menyandarkan lelahnya di pundakku. Atau perempuan yang sekedar menyapa kehadiranku. Maka, sepi cocok untukku.
Di kafe dekat senja—dua ratus meter dekat bibir pantai—ini, banyak keluh kesah yang ingin kusampaikan pada orang-orang. Seorang pelayan mendatangiku. Ia memakai baju putih berjas buka berwarna merah. Ia berjalan santai sambil menimpaliku pertanyaan, “Mau pesan apa, Tuan?”
“Aku pesan secangkir Ristretto,” ucapku padanya.
Pelayan itu hampir saja membuka buku menu. Namun, ia tak jadi membukanya karena aku telah lebih dulu mendahuluinya.
“Tunggu sebentar ya, Tuan,” pungkasnya.
Aku mengangguk.
Lantas aku memandang senja yang hadir. Awan itu mulai gelap; nampak temaram. Semburat surya perlahan menghilang. Inikah senja itu? Begitu indah dipandang. Kafe ini bernama kafe Senja. Mungkin karena senja selalu nampak hidup di ujung pantai barat itu, sehingga aku dapat merasakannya.
Namun, alangkah terkejutnya diriku saat menyaksikan kafe ini bergetar, seolah-olah sedang terjadi gempa. Benar saja. Kupikir, gempa sedang melanda daerah ini. Aku panik seketika, begitupula dengan orang-orang yang ada di sini. Mereka berlarian ke sana-ke mari. Tas selempang hitam kuangkat; aku berniat menyelamatkan diri.
Kulihat beberapa pengunjung berlari lintang pukang. Sebagian darinya ada yang menggandeng pasangannya dan sebagian lagi ada yang melompat ke jendela hingga jendela itu pecah. Ada juga seorang kakek sedang dituntun oleh anaknya—begitu kiraku. Mereka berjalan lambat untuk keluar dari kafe ini. Pelayan-pelayan itu juga pontang-panting. Mereka semua—yang ada di kafe ini—pergi menyelamatkan diri.
Salah satu atap di sebelah utara roboh. Di sana terlihat lubang besar yang menganga. Botol-botol minuman keras pecah berserakan. Foto-foto dan lukisan-lukisan jatuh ber-hamburan. Aku melihat retakan yang muncul di bagian barat kafe. Kupikir, kafe ini akan hancur lebur dan hanya menyisakan puing.
Anehnya, saat semua orang telah keluar, gempa mendadak berhenti. Tinggal aku sendiri yang tinggal—yang belum sempat keluar dari kafe.
Aku bingung. Mengapa ini semua terjadi? Apakah semua bermula dari kemunculan senja? Ataukah kehilangan senja yang sekejap pandang ditelan bulan? Atau mungkin semua karena diriku? Sebab diriku telah memesan sesuatu pada pelayan. Tidak. Aku hanya memesan secangkir Ristretto, bukan memesan sepi.
***
SEMUA orang akan mengenalku. Seorang lelaki pengangguran yang hanya menenteng tas selempang hitam yang berisi laptop. Aku adalah penyair yang lahir dari seorang ibu penjual gorengan. Namun, belum genap usiaku sepuluh tahun, perempuan yang meng-izinkanku untuk tinggal di dunia itu telah pergi dari dunia. Ia meninggalkanku sendirian di sini, begitu juga dengan suaminya yang telah lebih dulu pergi ke alam lain. Ia juga tak meninggalkanku adik.
Aku adalah penyair yang membenci sepi. Biarpun aku hidup dari kesepian, namun aku sangat membencinya. Aku selalu berjalan ke kota. Menyusuri setiap jalanan untuk sekedar mencari keramaian. Jikalau naskah puisiku dimuat di salah satu koran nasional, aku pasti singgah di kafe-kafe di sekitar kota. Di sana aku bakal memesan kopi dan keramaian. Sebab, aku suka keramaian.
Kejadian gempa di kafe Senja bukan yang pertama kalinya dalam hidupku. Kejadian-kejadian itu telah berlangsung sejak dulu, sejak aku mengenal puisi. Aku mengenal puisi saat usiaku sudah dua puluh tahun. Saat masih muda, aku bingung mau cari pekerjaan. Keluargaku telah habis tak tersisa dimakan semesta. Kini aku tak memiliki siapa-siapa lagi untuk membantuku mencari pekerjaan, hingga aku bertemu dengan Sunyi.
Sunyi adalah seorang lelaki separuh baya yang kutemui di pasar loak. Waktu itu, aku berniat untuk membeli buku sebagai teman hidupku. Seorang lelaki berambut panjang mendatangiku tanpa sebab. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Sunyi.
“Namaku Sunyi,” ucapnya, mengajakku berkenalan.
Aku menyalaminya. Lantas ia memberikan sebuah laptop kepadaku. Aku tak tahu mengapa ia begitu baik pada seseorang yang baru dikenalnya. Hanya ada satu kalimat yang masih kuingat kala itu.
“Kau adalah sepi. Dari sepi itu timbullah ramai, hingga pada akhirnya, setiap dunia akan terisi dengan keramaian. Semua itu berkat dirimu, sepi. Maka, ciptakanlah kesepian itu agar kau menemukan keramaian,” pungkasnya, sambil memberiku laptop.
Aku tak paham apa maksudnya. Tetapi, berkat laptop sederhana yang ia berikan padaku ini, aku jadi lebih sering menulis puisi. Iya, puisi-puisiku selalu laku di koran-koran nasional. Hal itu membuatku berpenghasilan walau tak menentu. Sampai sekarang, aku masih menulis. Entah kenapa, inspirasi terasa cepat keluar saat semua menjadi sepi.
Sunyi telah pergi entah ke mana. Ia adalah orang asing. Bahkan aku hanya mengenalnya sekilas nama. Kini, aku membuka laptop. Aku duduk di bibir pantai pagi-pagi. Pantai ini masih sepi dari pengunjung. Hanya ada beberapa orang di sini. Tepat pada pukul tujuh pagi, aku telah menciptakan keramaian lewat puisi-puisiku yang terlahir dari laptop ini. Dari selembar puisi itu, terlahirlah orang-orang dengan berbagai macam karakter.
Pantai ini mendadak penuh pengunjung. Aku bingung bukan main. Kenapa puisiku dapat memunculkan orang-orang itu? Bagaimana aku bisa melakukannya?
Keanehan terjadi lagi, kala senja kudapati muncul di langit-langit. Tatkala senja itu sirna, semua orang yang ada di dekat pantai sekejap menghilang. Rumah penduduk terlihat mulai lenyap dari pandangan. Pohon-pohon kelapa juga sirna. Sampah-sampah di sekitar pantai terangkat; terbang menuju langit. Air laut pasang. Semua yang ada di sini terangkat menuju ke langit. Aku bingung bercampur takut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Cepat-cepat kubuka laptop. Aku menulis puisi sedikit demi sedikit hingga terlahirlah beberapa puisi. Puisi-puisi ini kemudian kubaca satu per satu. Berharap darinya, timbullah keramaian, seperti apa yang telah kulakukan pagi tadi.
Dua ratus puisi kuciptakan malam ini. Sungguh aneh, kenapa aku bisa menciptakan puisi sebanyak itu dalam sekejap? Apakah semua itu karena sepi? Justru yang membuatku bingung lagi adalah perihal sepi yang memungut dunia ini. Sebanyak puisi yang kucipta dan kusenandungkan itu nyatanya tak mampu membuat keramaian.
Aku masih berada di bibir pantai ini sendirian. Malam belum berhenti memungut semua yang ada di sekitarku. Bahkan ia juga nampak akan memungut laptopku. Iya, laptopku seolah seperti ditarik oleh malam. Aku memegangnya erat-erat. Aku hampir tertarik malam. Kakiku terangkat. Tanganku terangkat ke atas memegang laptop. Aku ikut tertarik. Aku lenyap dari pantai ini; terbang menuju ke langit.
***
BAGAIMANA aku bisa tahu tentang sepi, sedangkan aku saja dipungut oleh malam. Sepi itu tak ada. Aku paling membenci sepi. Bahkan ketika Sunyi memberikanku laptop ini untuk kugunakan menulis, aku tak tahu dari mana asalnya ia. Lelaki yang tak kukenal itu pun juga telah sirna. Tetapi, aku seolah mendengar ucapannya samar-samar. Pada dimensi lain—yang aku pun tak tahu ada di mana ini—suara yang mirip dengan suara Sunyi itu berulang kali terdengar. Terakhir, ia seperti sedang berbicara pada sepi.
“Akulah sunyi yang berkuasa pada sepi. Semua orang akan tahu bagaimana malam telah memangsa dunia hingga jagat tak menyisakan apapun selain sepi. Dunia ini bermula dari sepi dan akan berakhir menjadi sepi. Terima kasih, Nak. Kau telah memesan sepi dengan puisi,” pungkasnya.
Bahkan, namaku sendiri sebenarnya adalah Sepi. []
Kota Gadis, Januari 2018